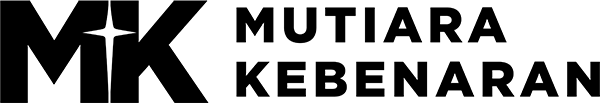Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik – Paulus Tarsus, 1 Kor 7:38
Kita hidup di dalam zaman dimana pernikahan memiliki prospek yang tidak begitu cerah. Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan, perasaan kesepian dan frustrasi yang melanda pasangan suami istri terus meningkat. Telah banyak tulisan dibuat untuk membahas betapa menyedihkannya zaman kita, apakah yang menyebabkan problem-problem pelik dalam pernikahan tersebut, dan bagaimana kita dapat meminimalkan dan bahkan mengatasinya. Dalam kesempatan ini saya tidak berminat untuk menambah panjang deretan tulisan-tulisan semacam itu. Paparan saya kali ini akan berfokus kepada satu pertanyaan yang paling mendasar saja tentang pernikahan, yaitu: untuk apakah sebenarnya kita menikah?[1] Buat apa repot-repot mengusahakan sesuatu yang sedemikian pelik untuk dibuat sukses sementara kita memiliki pilihan-pilihan lain untuk mencapai apa yang pada masa lampau hanya dapat dicapai dengan menikah (mis. memiliki anak, kehidupan seksual yang aktif tanpa perasaan bersalah dan rasa malu, keamanan finansial, status sosial, dan lain-lain)? Mengapakah pernikahan Kristiani masih patut diperjuangkan dan tidak tergantikan oleh bentuk-bentuk ikatan sipil[2] yang lain? Gereja harus mengakui bahwa praktik pernikahan yang kita jalankan hampir-hampir secara otomatis selama berabad-abad, sekarang ini bukanlah satu-satunya pilihan – bahkan juga bagi sebagian warga gereja yang memilih agar kehidupan privatnya tidak direcoki oleh orang-orang lain. Jadi, ini adalah waktu untuk merenungkan kembali secara lebih serius, dan merumuskan secara lebih terang bagi dunia ini mengapakah orang-orang Kristen masih saja melakukan berbagai praktik yang telah ketinggalan zaman tersebut. Khususnya, mengapakah kita masih saja melakukan praktik-praktik ‘kolot’ semacam pernikahan dengan satu pasangan (monogamy), relasi eksklusif tertutup (bukan open marriage di mana masing-masing pasangan sah-sah saja untuk punya relasi seksual dengan siapa saja asalkan diketahui dan disetujui bersama), berjanji saling setia sampai mati, saling menghargai, saling mengasihi, dan lain-lain hal muluk-muluk itu. Di dalam zaman dimana orang lebih terbuka kepada kelemahan-kelemahan manusiawi dan tidak lagi terlalu berharap bahwa manusia dapat memenuhi ideal-ideal yang dahulu dianggap dapat dicapai oleh para orangtua kita yang barangkali hidup di dalam zaman yang lebih sederhana, apa alasannya kita masih saja mempertahankan institusi pernikahan tradisional? Apakah yang ditawarkan oleh visi pernikahan Kristiani yang telah dianggap ketinggalan zaman tersebut? Dalam artikel ini saya ingin memaparkan secara garis besar mengapakah pernikahan Kristiani tersebut sesungguhnya menjanjikan apa yang diidam-idamkan oleh hampir setiap manusia, yaitu kasih, penerimaan, kepuasan hidup, pertumbuhan di dalam pengenalan diri yang sehat, dan juga tujuan hidup yang terarah ke luar dirinya.
Disklaimer
Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa saya BUKAN hendak mengatakan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara agar orang dapat mengalami dikasihi dan mengasihi, menjadi agen, model, dan saksi bagi datangnya kerajaan Allah. Tidak. Tuhan kita Yesus dari Nazaret itu sendiri tidak menikah, sementara tentu saja Dia membuka jalan bagi datangnya Kerajaan Shalom itu di bumi. Jelas orang-orang yang hidup menjomblo (single) di dalam ketaatan kepada Kristus sedang melakukan sesuatu yang baik, bahkan barangkali lebih baik, daripada orang-orang yang menikah (lihat pembahasan rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal yang ke 7). Yang saya hendak paparkan dalam artikel ini bukanlah bahwa menjomblo itu buruk, tetapi apakah panggilan mulia yang terkandung di dalam pernikahan Kristiani dan bagaimanakah panggilan itu dapat kita jalani di dalam zaman kita.
Secara singkat jawaban saya atas pertanyaan untuk apa menikah adalah untuk menjadi agen, model, dan saksi bagi datangnya shalom di bumi.[3] Hal ini akan saya kaitkan dengan tiga metafora tentang pernikahan, yakni pernikahan sebagai suatu usaha untuk mendirikan rumah, sebagai jalan salib yang penuh sukacita untuk menghidupi ketaatan pada Sang Raja-Sahabat-Mempelai, dan juga sebagai bagian dari kesaksian kita tentang menangnya Kristus atas kejahatan dan dosa di dalam konteks relasi antar-personal, antar-generasi, bahkan barangkali juga antar-kebudayaan di bumi ini. Saya akan melihat pernikahan Kristiani dalam kaitannya dengan tiga istilah: rumah, raja, dan ragi.
Rumah
Menikah adalah mendirikan rumah di bumi. Lewat pernikahan orang melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia di bumi, yaitu untuk menjadikannya sebuah ‘rumah’. Apakah perbedaan antara ‘ruang’ (space) dan ‘tempat’ (place) – ini analog dengan perbedaan antara ‘house’ dengan ‘home’ – kita di bumi adalah untuk menjadikan ruang-waktu yang ‘tidak bertuan’ ini menjadi tempat yang ‘homy’ – membuat para penghuninya merasa ‘kerasan’, diterima, dikasihi, dan dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan sejati seperti yang Tuhan selalu kehendaki. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi, Ia memberikan kepada kita sebuah tugas. Tugas seorang manusia di dalam dunia ini, menurut kisah di dalam kitab Kejadian 1-2, adalah untuk ‘memenuhi’ dan ‘menaklukkan’ ciptaan (agar tidak salah sangka kata ‘menaklukkan’ itu dapat dibaca sebagai: untuk bertanggung jawab atas ciptaan). Ini adalah sebuah panggilan untuk menjadikan hutan rimba dan padang gurun menjadi sebuah rumah yang homy.
Dunia ini adalah tempat yang brutal. Anda hanya perlu menyaksikan apa yang terjadi di dalam kelas-kelas pre-school tempat di mana anak-anak kecil yang menjadi cermin dari rumah tempat mereka bertumbuh berkumpul. Dunia anak-anak bukan hanya diwarnai tawa canda ceria, tetapi juga oleh realitas bullying dari anak-anak yang bertubuh lebih besar, penghinaan dan penolakan yang kerap kali mereka alami dari guru-guru atau anak-anak yang lain, rasa malu, minder, bahkan kekerasan domestik dan pelecehan seringkali kita jumpai di dalam dunia kanak-kanak. Realitas ini mencerminkan bahwa dunia ini kekurangan rumah, tempat di mana anak-anak, generasi penghuni masa depan itu, dapat tumbuh kembang di dalam segala kerapuhannya tanpa dimanipulasi, dieksploitasi, ditakut-takuti, dan hal-hal menyedihkan semacamnya. Bukan hanya kanak-kanak, seringkali para pasangan suami-istri itu sendiri seringkali masuk ke dalam pernikahan dengan membawa-bawa beban masa lampau mereka yang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kehidupan pernikahan. Trauma-trauma masa kanak-kanak atau remaja di satu sisi dapat membebani rumah tangga yang baru dengan beban sejarah, dan tragisnya, keluarga yang baru ini seringkali tidak menjalani narasi yang baru juga di dalam kehidupan mereka. Terkadang kisah kelam yang lama dapat terulang dalam pola-pola yang hampir serupa dengan pemain yang berbeda dalam sebuah pernikahan. Di sini sebuah pernikahan Kristiani terpanggil untuk memutuskan siklus jahat narasi duniawi yang tragis itu dan menggantinya dengan drama penebusan yang memberikan pengharapan bagi kita, orang-orang lemah ini. Pernikahan Kristen adalah salah satu tempat seperti itu: menyediakan konteks bagi lakon drama di mana di dalam Kristus dan melalui pekerjaan Roh Allah kebenaran, keadilan, pengampunan, cinta kasih, kesabaran, dan kesetiaan, dapat menang atas kejahatan, pengkhianatan, bully, dendam kesumat, kepura-puraan, dan manipulasi. Sekali lagi, saya tidak hendak mengatakan bahwa hal-hal ini tidak dapat terjadi pada orang-orang yang tidak menikah. Tetapi ada konteks yang lebih khusus bagi mereka yang mengikat janji permanen untuk setia, mengasihi, merawat, merayakan, dan berbagi hidup dengan satu pasangan di dalam pernikahan untuk mengalami sendiri bagaimana berperang dengan sisi-sisi tergelap dalam hidup kita yang dapat terpancing keluar dalam konteks kehidupan intim dengan satu orang dalam waktu berpuluh-puluh tahun. Seperti juga relasi persahabatan yang mendalam tak dapat timbul jika kita hanya bertemu dan bersapa dengan kawan gereja seminggu sekali selama beberapa menit. Tidak akan ada rasa benci ataupun cinta yang terlalu serius dapat muncul dari relasi yang sedangkal itu. Demikian dalam pernikahan kita akan mendapati relasi-relasi yang lebih mendalam, lebih serius – di dalam gelap dan terangnya. Ini adalah kesempatan juga, di dalam rumah yang kita dirikan itu, terdapat kesempatan untuk kita berjumpa dengan diri kita yang lebih mendalam, lebih gelap, tetapi juga membuka kemungkinan untuk disadari dan dipulihkan ke dalam kemuliaan yang seharusnya oleh pekerjaan Roh Tuhan melalui pergesekan dengan orang lain, yakni pasangan dan anak-anak kita.
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. – Ef. 2:1-2
Di dalam rumah itu terdapat kesempatan untuk menjadi suami, istri, ayah, ibu, dan menjadi anak. Dalam menjalani peran-peran yang dimungkinkan oleh pernikahan ini orang ditantang untuk melangkah bersama Yesus di dalam jalan salib. Jalan dimana kedagingan kita, keduniawian kita, diharapkan untuk semakin mengecil dan mati – sementara manusia baru yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi semakin nyata. Dalam pernikahan itu ada kesempatan bagi kita untuk melihat kekuasaan Tuhan dalam mengatasi segala dosa dan kejahatan yang begitu kuat mencengekeram kita melalui pekerjaan kasih yang penuh pengorbanan. Kasih itu menyembuhkan, dan di dalam pernikahan ada ruang untuk mengalami dikasihi dan mengasihi secara lebih intensif dan ekstensif. Di dalam pernikahan terbuka kesempatan untuk mengalami ‘mengasihi orang lain (yaitu: istri atau suamimu) SEBAGAI diri sendiri, bukan hanya SEBAGAIMANA diri sendiri (bnd. Ef. 5:28)
Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Ef 2:28
Paulus bukan hanya menyuruh suami-suami Kristen untuk mengasihi istri-istri mereka, tetapi ia mengatakan bahwa suami-suami yang mengasihi istri-istri mereka SEDANG MENGASIHI TUBUHNYA SENDIRI. Seperti dikatakan Augustinus, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mengasihi diri sendiri – karena kita diciptakan dengan insting bawaan untuk mengasihi diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan juga tak pernah menyuruh kita untuk bernapas, makan, minum, dan beristirahat – kita PASTI melakukannya, sebab kita masing-masing mengasihi diri sendiri. Tidak ada yang ssalah dengan itu. Tuhan menciptakan kita demikian. Walaupun tentu di dalam kejatuhan kita, kasih kepada diri sendiri itu merosot menjadi kasih yang SEMATA-MATA tertuju kepada diri sendiri dengan mengorbankan kasih kepada Allah dan orang-orang lain (sebuah anti-tesis dari keterciptaan kita semula). In curvatus in se inilah masalahnya. Dalam kebanyakan pernikahan Tuhan menyediakan anak tangga yang lebih mudah bagi kita untuk mengasihi sesama yang sungguh-sungguh berbeda, yaitu Dia memberikan kepada kita SESAMA YANG LEBIH MUDAH UNTUK DIKASIHI: The lovely one, your bride (or groom). Barangkali Tuhan mengatakan, “Apa? Kau menolak untuk mengasihi musuhmu? Walaupun dia itu saudaramu sesama manusia dan Kristus juga telah membelinya dengan darah-Nya yang mahal itu? OK, Aku akan memberimu yang lebih mudah dahulu. Sebelum mendaki Semeru berlatihlah mendaki bukit pendek ini. Kasihilah istrimu (yang kau pilih sendiri itu)”. Lalu jika Tuhan mengaruniakan anak Ia pun menitipkan sesuatu yang lovely dan ‘lebih mudah’ untuk dikasihi (karena lebih mirip diri kita) yaitu anak-anak kita. Kasihilah yang lebih mudah ini dahulu agar engkau lebih siap untuk mengasihi orang-orang yang lebih sulit. Bukankah Tuhan kita penuh kemurahan?
Walaupun seringkali terlihat remeh, tetapi kasih di dalam keluarga-keluarga Kristen ini dapat memiliki efek yang dahsyat. Kita mengetahui bagaimana masyarakat Romawi yang bermusuhan dengan para pengikut Yesus pada tahun-tahun awalnya, secara berangsur-angsur dimenangkan bagi Kristus. Tidak sampai tigaratus tahun sejak kematian dan kebangkitan Yesus, pengaruh orang-orang Kristen ini semakin meluas di dalam masyarakat Romawi kuno – sampai akhirnya kepercayaan aneh mengenai datangnya kerajaan Allah melalui kematian dan kebangkitan seorang Mesias yang dianggap gagal dan palsu itu memenangkan hati banyak orang Romawi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Saya kira peranan keluarga-keluarga Kristen tidaklah kecil di sini. Saya dapat membayangkan istri-istri Kristen menghadirkan sesuatu yang berbeda bagi suami-suami Romawi mereka, juga perempuan-perempuan Romawi, dapat melihat jelas bahwa ada sesuatu yang hilang dari pernikahan mereka sendiri jika dibandingkan dengan apa yang dialami perempuan-perempuan Kristen purba ini dalam relasi mereka dengan suami-suami mereka yang percaya. Saya kira proyek ‘membangun rumah’ di sini jelas tidak terbatas pada pengejaran kebahagiaan domestik di antara keluarga Kristen itu sendiri, tetapi secara inheren berkaitan dengan orientasi keluarga Kristen itu sendiri yang hendak menghadirkan shalom dalam lingkungan mereka melalui tindakan-tindakan kasih yang nyata.
Raja
Menikah adalah menghidupi datangnya Kerajaan Allah. Di dalam usaha mendirikan rumah itulah kita mengakui TUHAN, Sang Pencipta, sebagai Raja atas segala yang ada, atas segenap hidup kita. Pernikahan Kristiani menyaksikan siapakah yang menjadi raja atas hidup anak-anak Tuhan. Di dalam sebuah pernikahan Kristiani yang menjadi raja bukanlah suami atau istri, bukanlah anak-anak atau mertua, bukanlah orang tua atau siapapun, atau uang, kekuasaan, atau seks, atau kehormatan keluarga. Yang menjadi raja dalam sebuah pernikahan Kristiani adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menyatakan diri dan kerajaannya di dalam Yesus dari Nazaret. Seperti apa kira-kira pernikahan dimana Yesus Kristus menjadi raja? Karena Yesus adalah raja yang melayani, kebenaran yang membebaskan, jalan yang menuju kepada hidup, maka tidak heran di dalam pernikahan Kristiani apa yang dikejar bukanlah dominasi kekuasaan, kestabilan ekonomi, daya tarik seksual, atau manipulasi lewat segala muslihat psikologis. Di dalam pernikahan Kristiani kita dapat melihat bagaimana kasih merajalela, karena Tuhan adalah kasih, pengampunan menjadi jalan bagi masa depan relasi yang buntu, karena Tuhan mengampuni kita di dalam Yesus Kristus, kebenaran dan keadilan dijunjung tinggi karena Yesus adalah Sang Kebenaran itu sendiri. Jika jalan yang seperti ini kita lalui, sementara jalan ini dapat dilalui oleh siapapun, tidak ada gerbang toll yang menuntut kehebatan setinggi langit untuk kita dapat melaluinya, maka kita akan menyaksikan Tuhan menjadi Raja di dalam pernikahan manusia. Pernikahan Kristiani harus diletakkan di dalam konteks sejarah penebusan, misi gereja, dan panggilan hidup orang percaya. Pernikahan bukanlah demi pernikahan itu sendiri, melainkan demi langit dan bumi yang baru dimana kehendak Tuhan dilakukan di bumi, seperti di dalam surga. Yang paling penting di sini bukanlah si suami, si istri, anak-anak, atau apa kata orang – tetapi kemuliaan Tuhan yang terpancar (atau tidak) melalui relasi-relasi di dalam pernikahan itu.
Ragi
Dalam gambaran ketiga yang saya pakai, pernikahan itu menyaksikan datangnya Kerajaan Allah sebagai ‘ragi’ yang bekerja secara diam-diam – secara rahasia – untuk menyatakan datangnya Shalom itu secara nyata ke tengah ciptaan. Lewat pasangan-pasangan Kristen kasih itu akan semakin memenuhi dunia ini. Jika pasangan-pasangan itu dikaruniai anak-anak oleh Tuhan, maka ada kesempatan bagi pasangan yang belajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling setia itu untuk membesarkan anak-anak mereka itu di dalam sebuah rumah di mana ada keadilan, kebenaran, dan cinta. Kebanyakan kita lahir dan dibentuk di dalam sebuah rumah tangga. Seperti apakah diri seorang manusia seringkali mencerminkan seperti apakah rumah tempat ia bertumbuh. Anak-anak yang tumbuh kembang dalam keluarga yang berusaha untuk mengasihi Tuhan dan sesama akan memenuhi dunia ini dengan ragi kerajaan Allah itu. Dengan demikian, generasi demi generasi ragi kerajaan Shalom itu akan makin mengembangkan adonan masyarakat dan ciptaan ini untuk mengusir keluar lebih banyak lagi bayang-bayang dosa dan kejahatan dan mengisi ciptaan dengan aneka ragam kebaikan, sukacita, kegembiraan, keadilan, dan keindahan. Sebagaimana ragi tidaklah berguna bagi dirinya sendiri, demikian pernikahan Kristiani harus menjadi saluran berkat bagi lingkungannya – bukan berkutat dengan kebahagiaan (atau ketidakbahagiaan) nya sendiri. Karena yang dipertaruhkan dalam sebuah pernikahan Kristiani adalah misi penyelamatan Tuhan atas langit dan bumi, maka jatuh bangunnya sebuah pernikahan orang percaya juga bukan melulu urusan privat mereka berdua, melainkan urusan gereja juga – bukan karena gereja mau kepo karena kurang kerjaan – tetapi karena pernikahan Kristiani adalah suatu showcase bagi datangnya kerajaan Shalom. Itu sebabnya di dalam ibadah pemberkatan nikah, para hadirin turut mendoakan dan mendukung janji yang diucapkan oleh kedua pasangan – mereka turut bertanggungjawab di dalam menyukseskan pernikahan kawan-kawan mereka sesama orang percaya.
Simpulan
Dari pembahasan di atas saya berharap menjadi jelas bagi para pembaca sekalian bagaimana visi pernikahan Kristiani masih sangat relevan bagi kita semua di dalam zaman yang semakin sekuler ini. Pernikahan Kristiani itu bukan melulu untuk memuaskan diri sendiri atau pasangan kita, bukan respon atas ketakutan-ketakutan kita (takut diejek, takut kesepian, takut tidak bahagia, dst), bahkan bukan terutama demi kehormatan keluarga, komunitas marga, suku, atau bahkan gereja atau Negara. Orang-orang Kristen sebaiknya menikah bukan karena takut, bukan karena ingin bahagia, bukan karena lelah dirongrong terus oleh mereka yang kepo, dan juga bukan karena ingin memperbesar kemuliaan gereja atau Negara atau apalah. Orang-orang Kristen seharusnya menyadari bahwa mereka menikah (atau hidup single) demi kasih kepada Allah dan sesama, demi Kerajaan Shalom yang telah, sedang, dan akan datang di dalam Kristus Yesus itu.
Jakarta, 3 Februari 2018
J.S. Lima
[marriage is holy and honorable and should not] be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God – Book of Common Prayer (1892)
[1] Pertanyaan ‘mengapa menikah’ sepertinya sia-sia. Untuk apa mempertanyakannya? Orang toh akan tetap menikah (atau tidak) terlepas dari apapun jawaban dari pertanyaan tersebut. Orang normal pada umumnya kan tidak pergi kepada filsuf atau teolog untuk mencari jawaban atas pertanyaan tidak normal tersebut sebelum mereka pergi menikah! Tentu saja orang menikah karena terdorong untuk melakukannya. Dorongan-dorongan untuk menikah itu biasanya berasal dari tekanan sosial, kebutuhan seksual yang hendak disalurkan lewat cara-cara yang ‘legal’, kebutuhan akan ‘teman hidup’, dan barangkali juga kebosanan akan modus hidup menjomblo yang sudah dijalani bertahun-tahun, serta mungkin juga bagi beberapa orang, rasa takut ketinggalan (kiasu). Menikah itu juga adalah cara pamungkas untuk membungkamkan mulut orang-orang kepo yang selalu bertanya: “Kapan married?” “Mana nih undangannya?” dan lain-lain pertanyaan membosankan dari kids zaman old. Di belahan dunia sini populasi orang-orang kepo masih cukup banyak dan salah satu cara yang sering dilakukan untuk membuat mereka bungkam adalah dengan memenuhi permintaan mereka (yang nggak jelek-jelek amat itu). Been there, done that, let’s move on.
[2] Tentu saja ‘pilihan-pilihan’ lain ini (mis. ‘kumpul kebo’ atau samen leven, atau juga open marriage atau Hubungan Tanpa Status, Teman Tapi Mesra, dst) masih dicibir oleh mereka yang ‘taat beragama’ dan barangkali merasa diri lebih baik dari orang-orang ‘sekuler’ namun dalam kenyataannya, di dalam masyarakat sekuler, orang semakin terbuka pada pilihan-pilihan alternatif ini.
[3] Istilah ‘shalom’ yang dipakai sebagai ucapan salam dalam berbagai kebudayaan di Timur Tengah mengandung suatu harapan bahwa suatu hari kelak perang akan berhenti, damai akan datang di bumi. Tetapi damai ini bukan hanya sekedar gencatan senjata belaka, melainkan hadir bersama dengan keadilan, cinta kasih, kemakmuran, kegembiraan, dan segenap kepenuhan makna kehidupan – bukan hanya bagi mereka yang kuat, kaya, dan sehat seperti sekarang ini, tetapi bagi setiap orang yang berkenan kepada Allah – bahkan bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi segenap ciptaan. Kita dapat menjumpai pengharapan akan datangnya Shalom ini di dalam kitab-kitab para nabi, Mazmur, dan juga di dalam Perjanjian Baru (mis. gambaran mengenai keadaan umat Tuhan yang dipulihkan dalam Yesaya 65, Mazmur 36: 6, Roma 8: 18-22).